By: Martin Aleida
IRAMANI namaku. Umurku tujuh-puluh dua. Tak usah terlalu panjang aku menyebutkan siapa aku. Cukup, katakanlah semua kamp konsentrasi atau penjara paling bengis yang pernah kau tahu. Dan itu adalah juga aku.Usiaku habis percuma ditelan tembok-tembok penjara yang dekil dan menyesakkan. Dan ketika aku ditendang keluar dari sel, aku masih harus menanggungkan perlakuan sewenang-wenang dari satu rezim yang didukung oleh manusia yang terus-menerus kupertanyakan dalam hati, dari manakah mereka mewarisi perangai lalim yang telah memencilkan aku selama tiga belas tahun di dalam kurungan, terutama di penjara wanita Pelatungan. Hanya karena aku seorang istri. Ya, seorang istri. Jika inilah kodrat yang harus kuterima sebagai wanita, maka dia telah kujalani dengan sempurna.
Tetapi, bagaimanakah aku harus menjelaskan kepada Tatiana, anakku yang terkecil, yang harus mengikuti aku ke sel penjara mana saja aku dicampakkan bagaikan sampah, yang buat kompos pun tak berguna. Rezim juga telah memperkosa naluri Tatiana, yang selalu ingin menyusu di dadaku, sebagai siksa tambahan bagi ibunya. Telah kubaca berpuluh kali catatan harian Anne Frank. Bisa kubayangkan, ketika larsa sepatu pasukan Nazi berdentam mendekati lemari persembunyiannya, tahulah dia bahwa ajalnya sudah sedekat bendul pintu. Terlahir sebagai Yahudi, dia dipaksa menemukan nasib sebagai buruan. Gadis cilik itu masih lebih mujur dari kami. Dia mungkin telah musnah bersama kepulan gas beracun yang disemburkan ke dalam kamar pengasingannya. Sedangkan kami, aku dan anakku, masih terus berbagi degup jantung, menjaga nyawa, sekalipun sebenarnya kami sudah tersingkir dari keberadaan sebagai manusia yang hidup.Sudahlah, katamu melerai perasaanku. Lupakahlah, Ir Penderitaanmu akan larut dibasuh waktu, begitu kau berupaya menawarkan dendamku.Aku belum bisa menerima bujukanmu itu. Tapi, baiklah kudiamkan saja dulu galau penolakan dari dalam hatiku.
Belasan tahun dikucilkan di dalam sel penjara bisa kutanggungkan, mengapa memendam rasa aku tak kuasa.Tadi pagi aku bangun dengan perasaan yang lain sama sekali. Dalam empat-puluh tahun belakangan ini, tak pernah aku memiliki perasaan sebegitu riang. Membanding-banding, aku teringat bagaimana rasanya pada saat aku melahirkan anakku dulu. Ngeden yang mencemaskan berakhir dengan ketenteraman hati begitu melihat Tatiana yang merah rebah di sampingku. Rasa-rasanya seperti itulah kebahagiaan yang membendung perasaanku sekarang.Aku mengenakan pakaian terbaik. Duduk mengiringi naiknya matahari pagi. Bertambah nyaman rasanya di beranda sesempit ini ketika daun-daun kering berlarian menyentuh ujung-ujung kuku kakiku. Kemarin, ketika aku pulang dari kantor kelurahan, mengambil kartu tanda pendudukku, sudah kupuaskan sepuas-puasnya mata dan hatiku dengan KTP yang baru ini. Rasanya, keterangan diri yang mungil, dan dibalut plastik mengkilap itu, telah memberikan kegembiraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hari ketika aku digelandang keluar dari Pelatungan, lebih dua puluh tahun yang lampau.
Kalau kuingat-ingat, tahulah aku bagaimana kebahagiaan begitu cepat kehilangan semaraknya dalam perjalanan waktu yang panjang. Ah, senangnya mengamat-amati KTP ini. Permukaannya yang mengkilap. Membersitkan kebanggaan. Aku seperti telah menemukan harga diriku kembali. Dunia di luar diriku kini telah menempatkan aku kembali sebagai warga biasa. Lihatlah, namaku ditulis dengan ejaan yang benar. Dengan huruf-huruf hitam yang rata. Pastilah dia diketik dengan menggunakan komputer. Mesin kejayaan manusia yang baru. Bukan mesin tik tua. Dia begitu ringkas sebagai pernyataan kehadiran seseorang di dalam masyarakat.
Memang, ada yang mengatakan kartu ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mendasar manusia. Hak bergerak bebas. Karena KTP merupakan perangkat kekuasaan untuk mengamati gerak-gerik warganya. Orang jadi tak bisa bebas bergerak tanpa ada mata yang mengawasinya. Sama dengan sapi yang harus membawa cacat yang ditinggalkan besi merah yang ditancapkan di punggungnya ke manapun dia merumput dan memamah-biak. Tapi, aku tidak termasuk yang hanyut dalam sikap seperti itu. Karena aku memang seorang wanita yang terbuang bersama ribuan orang lain yang senasib. Kalau KTP ini dianggap sebagai kebejatan penguasa, apalagi yang akan dikatakan begitu melihat simbol yang diterakan di pojok kartu ini? Tiga huruf yang menyengsarakan, mematikan...
Besarnya kartu ini hanya tiga jari. Tetapi, betapa sempurna kelegaan hati yang diberikannya. Di pojok kanan atasnya sudah tidak tertera hukuman yang harus kupikul sampai pun aku berangkat ke liang lahat: ETP, eks tahanan politik. Masih kuingat, tanganku gemetar ketika menyerahkan KTP lama kepada orang kelurahan. Aku merasa noda yang dilekatkan pada diriku seperti sudah ditempatkan di dalam perahu perlambang dosa, dan sudah dilepas ke laut yang dalam. Aku tidak sendiri menjalani nasib seperti ini. Dan tak bisa kau bayangkan betapa tertekannya perasaan dipencilkan seperti itu. Bukan aku saja yang harus melata karena cap itu. Juga anak-anakku. Pintu tertutup buat kami untuk memasuki kehidupan yang normal. Kami semua benar-benar menjadi paria karena cap yang melekat di pojok tanda pengenal itu. Lebih dari dua-puluh tahun aku mengantungi hukuman itu. Hanya karena aku seorang istri.
Aku tak tahu apa kesalahan yang dilakukan suamiku menjelang bencana tahun 1965, sehingga dia harus dilenyapkan. Dan istrinya, anak-anaknya yang masih merah, harus menderita. Padahal aku hanyalah seorang istri. Dan buatku, suami adalah seseorang kepada siapa aku berbagi. Naluri mengajari aku untuk setia pada kodrat fisikku, untuk mendekatkan anak-anak pada kedewasaan. Aku tidak dengan sengaja menjauhi gelanggang politik. Aku hanya tidak tertarik. Kupikir aku telah memberikan sumbangan yang besar kepada cita-cita suamiku, apabila aku bisa memegangi tangga kalau dia hendak menjangkau buku yang terletak di deretan teratas dari rak bukunya. Bisa membersihkan kaca-matanya sementara dia mandi. Dia sendiri sudah merasa puas kalau aku mau turut diajak ke kantornya. Terkadang, dia mengiming-iming akan mampir membeli masakan Tionghoa kesukaan kami dalam perjalanan pulang dari kantornya. Sesungguhnya, aku malu untuk mengatakan bahwa dia tetaplah seorang yang hangat, walaupun politik telah mengambilnya dari sisiku.Ketika aku ditanyai berbagai interogator militer sejauh mana keterlibatanku dalam kegiatan suamiku itu, aku jawab bahwa aku hanya menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya, menulis editorial di koran yang dia pimpin. Dengan rasa bangga kukatakan bahwa dia tak pernah kehilangan kata-kata ketika berhadapan dengan mesin tiknya. Masih kuingat, beberapa kali aku dipanggilnya supaya mendekat, dan meminjam penitiku untuk mencongkel daki yang melekat di huruf-huruf mesin tik.
Cuma meminjamkan peniti, dan aku harus menerima nasib sebagai orang buangan selama tiga-belas tahun. Para penyelidik itu tidak percaya bahwa aku hanya sekadar menemani suamiku mengetik editorial koran. Aku hanya duduk menunggu suamiku yang sedang menulis. Duduk sambil merenda. Kadang-kadang aku ditemani adik iparku. Tetapi, mereka tidak percaya. Dan mereka berharap aku akan berkhianat terhadap suamiku kalau aku disekap sampai ke ujung zaman. Dengan berbuat begitu, mereka malah telah memberikan pelajaran yang baik bahwa kejujuran tak punya tempat berlabuh dalam kezaliman yang mereka puja.Kembali kutatapi KTP yang baru kuterima ini. Wajahnya yang licin bersih. Lihatlah manisnya coat of arms dengan garis-garis merah di pojok kirinya.
Aku merasa memperoleh kebebasan yang kedua kalinya setelah beberapa kali kuyakinkan mataku bahwa tiga huruf kapital yang hitam dan buruk itu sudah disingkirkan dari pojoknya. Sanak famili yang cemas-cemas harap datang merubung ketika aku pulang dari Pelatungan. Kini, aku hanya sendirian merayakan kebebasan ini. Ditemani daun-daun kering yang menggamit-gamit ujung jari kakiku.Tiba-tiba daun pintu berderak di belakangku. Dan sebuah pertanyaan menghentikan monologku dalam diam.
"Sedang apa, Bu?," tanya Tatiana. Aku tidak hanya kaget, tetapi juga malu. Tanganku tak lepas dari KTP.Berderai kedua tangannya memelukku dari belakang. Memberikan kecupan persis di ubun-ubunku yang disaput uban yang tipis-tipis. Begitulah caranya membujuk hatiku.Perilakunya itu membuat jariku tergerai, dan matanya menangkap apa yang telah membuat perubahan besar dalam diriku pagi ini. Aku sambut tangannya. Mata Tatiana bolak-balik dari mataku ke KTP yang tergeletak membujur di tapak tanganku. Dia berlutut sembari terus melihat kartu yang alit itu. Seperti tak percaya pada apa yang terpantul ke matanya. Mulutnya agak ternganga. Jari-jari tangannya memagari bibirnya. Meskipun tidak dia ucapkan, aku tahu dia terperanjat melihat pojok KTP itu bersih, begitu murni, begitu membebaskan, dan terang sebiru laut. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, dia sedang bertarung dengan pertanyaan bagaimana tiga huruf yang jahat itu sudah tidak nongkrong lagi di pojoknya yang buruk. Huruf-huruf yang juga telah membuat dirinya sebagai tidak ada, walaupun ada. Begitu lama dia meletakkan hatinya pada secarik kartu yang membawa keajaiban itu.
Dia tetap berlutut, memegangi dengkulku. Dia seperti baru keluar dari terowongan yang gelap dan panjang. Dan dia menikmati pesona cahaya yang mengapung di depan, yang ditebarkan KTP itu. Tapi, dia cuma diam. Tak berkata barang sepenggal. Membisu seribu laut.Kuceritakan kepadanya mengenai keberangkatanku ke Solo beberapa waktu yang lalu. Terakhir kali aku pergi adalah untuk menyelesaikan penjualan sebidang tanah warisan ayahku. Dan uangnya kugunakan untuk menyingkirkan ETP yang terus-menerus mengepung, membelenggu, hidup kami. Kupikir inilah saatnya untuk menebus pembebasan yang terakhir sebelum aku mati. Aku pergi ke kantor kelurahan beberapa kali, sampai aku menemukan orang yang mau membantu menguruskan sampai aku memperoleh KTP yang bersih, di mana noda ETP yang mengejar-ngejar diriku, diri kami, tersingkir. Dan aku mau membayar dalam jumlah berapa saja."Jadi Ibu menyogok untuk KTP ini?!" Tatiana membelalakkan mata.Aku terpaku.
"Ibu menghabiskan jutaan rupiah untuk ini?! Perbuatan sia-sia...!"Aku tahu dia menahan amarah ketika mengatakan bahwa sogok-menyogok sudah bukan menjadi milik zaman anak-anak muda sekarang ini. Dan tanda penderita lepra yang berlambang ETP itu sudah dihapuskan pemerintah. Gong sudah ditalu. Siksa itu harus diakhiri. Karena Presiden Republik yang sekarang ini, ketika dia masih seorang kiai yang buta dengan hati yang baik setinggi langit, telah diterangi Tuhan pikirannya untuk meminta maaf atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang seperti aku ini."Uang jutaan itu kan bisa dijadikan Mas Jati modal berjualan. Mbak Rin bisa membuka toko obras. Mbak Win bisa melanjutkan sekolahnya. Mas Awang bisa membuka bengkel... Bisa... bisa... Ibu telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Sesuatu yang percuma..."
Tatiana seperti meratap. Dia anakku yang paling bungsu. Aku tahu hatinya luka, sangat terluka.Aku cuma diam. Terasa jarinya seperti tak mau melepaskan lututku. Aku tahu, di dalam hati dia meratapi kebodohanku. Tapi, aku tak menyesal. Takkan.Bertahun-tahun aku menanti sejak para penguasa mengumandangkan ETP itu tak diperlukan lagi. Tetapi, hukuman yang batil itu masih saja menghantu di pojoknya. Momok itu tetap berjaga-jaga di sudut KTP-ku. Sampai tanganku sendiri yang harus mengenyahkannya dari situ. Kalau tidak, berapa dasawarsa lagi aku harus meringkuk di kungkungan? Waktu telah mengajariku bahwa siapa pun tak bisa membuat kata-kata menemukan kenyataan yang dijanjikannya. Aku tak bisa menunggu. Kepercayaanku timpas sudah...

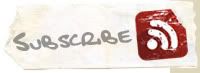
Comments (0)